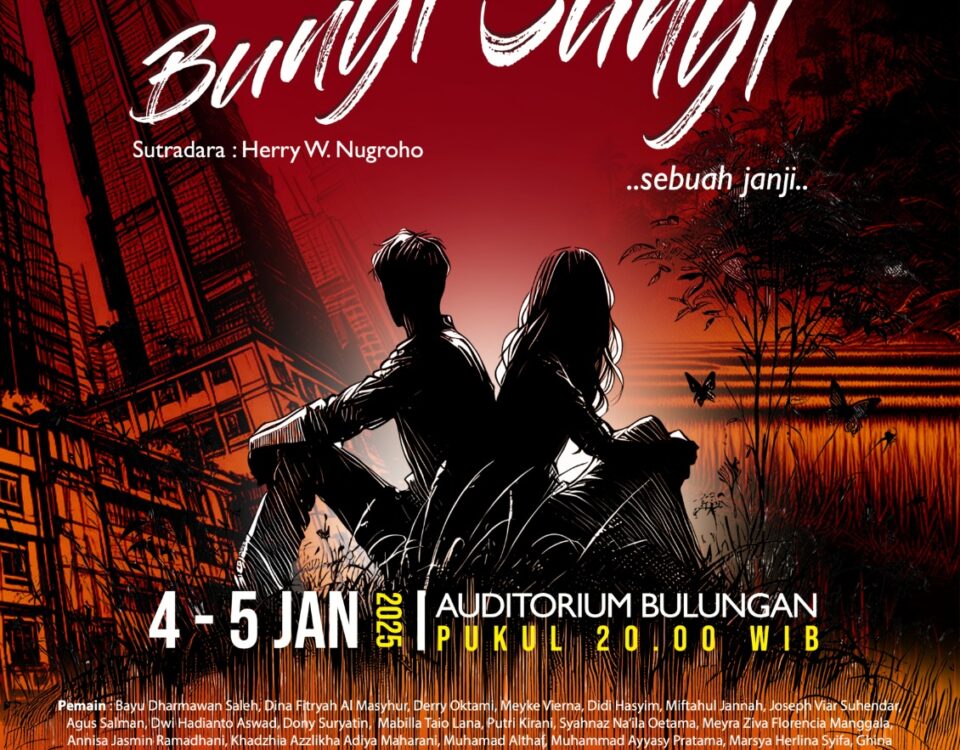SUKARNO muda semasa menempuh pendidikan menengah di Hoogere Burgerschool, nyantrik di kediaman Umar Said Cokroaminoto di Peneleh Gang 7, Surabaya. Raja Jawa tanpa Mahkota ini rajin berkeliling negeri menyambangi anggota Sarekat Islam, sambil kemudian berpidato. Menyampaikan gagasannya kepada rakyat banyak secara mangkus. Sukarno menyaksikan penampilan luarbiasa induk semangnya itu, lantaran terbiasa nderek. Hanya saja, anak muda yang satu ini punya versi lain dalam menenggang gurunya, “Pidato Pak Cok berbobot, tapi menjemukan.”
 Menurut yang kami nukil dari otobiografi Bung Karno: Putra Sang Fajar, “Kamarku tidak pakai jendela sama sekali. Tidak berpintu. Kamar itu sangat gelap, sehingga aku terpaksa menyalakan lampu terus menerus, bahkan saat siang hari. Di duniaku yang gelap ini terdapat sebuah meja reyot tempat menyimpan buku, sebuah kursi kayu, sangkutan baju, dan sehelai tikar pandan. Tiada kasur dan bantal.”
Menurut yang kami nukil dari otobiografi Bung Karno: Putra Sang Fajar, “Kamarku tidak pakai jendela sama sekali. Tidak berpintu. Kamar itu sangat gelap, sehingga aku terpaksa menyalakan lampu terus menerus, bahkan saat siang hari. Di duniaku yang gelap ini terdapat sebuah meja reyot tempat menyimpan buku, sebuah kursi kayu, sangkutan baju, dan sehelai tikar pandan. Tiada kasur dan bantal.”
“Dengan berdiri di atas mejaku yang reyot aku larut oleh perasaanku. Aku mulai berteriak. Selagi aku berpidato dengan suara keras di kamar yang kosong itu, kepala-kepala berjuluran keluar pintu, mata-mata tampak melotot, dan terdengar suara anak-anak muda berteriak dalam gelap: “He, No, kau gila? Ada apa… He, apa kau sakit?” Kemudian teriakan itu berubah menjadi, “Ah, tidak ada apa-apa. Hanya si No mau menyelamatkan dunia lagi.” Satu demi satu pintu-pintu menutup kembali, dan aku dibiarkan sendiri dalam kegelapan.”
“Selagi aku tumbuh dewasa, duniaku itu semakin lebar, mencakup pula kawan-kawan dari Cokroaminoto.”
“Setiap hari para pemimpin dari partai lain atau pemimpin cabang Sarekat Islam datang bertamu, dan setiap kali mereka tinggal selama beberapa hari. Sementara anak-anak kos yang lain keluar menyaksikan pertandingan bola, aku duduk di dekat kaki orang-orang ini dan mendengarkannya. Kadang kala aku berbagi tempat tidur dengan salah seorang pemimpin itu dan berbicara dengan mereka hingga waktu fajar.”
“Aku senang bila tiba waktu makan. Kami makan bersama sebagai satu keluarga, jadi aku dapat menyantap hidangan sekaligus meresapkan pembicaraan politik. Pada waktu para tamu bersantai di sekeliling meja, aku kadang-kadang berani mengajukan pertanyaan. Para mahaputra ini–putraputra besar dari rakyat Indonesia–tidak mengacuhkanku karena aku masih anak-anak. Suatu kali mereka membahas masalah kapitalisme dan barang² yang diangkut dari negeri kami untuk memperkaya Belanda.”
Saat itulah aku bertanya pelan, “Berapa banyak yang diambil Belanda dari Indonesia?”
“Anak ini selalu ingin tahu,” kata Pak Cok, dan kemudian menjawab, “’De Verenigde Oost Indischee Compagnie mengeruk atau mencuri–kira-kira 1800 juta gulden dari tanah kita setiap tahun untuk memberi makan Den Haag.”’
“Apa yang tersisa di negeri kita?” tanyaku, kali ini lebih keras sedikit.
‘“Rakyat tani kita yang bekerja mandi keringat mati kelaparan karena hanya mendapat penghasilan sebenggol sehari,”’ kata Alimin, orang yang memperkenalkan Marxisme kepadaku.
“’Kita menjadi bangsa kuli dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa,”’ sela kawannya yang bernama Muso.
Seorang wartawan asing terkemuka dan banyak menulis buku tentang negarawan besar, menyatakan pidato Sukarno adalah, “a delicately balanced proportion of dignity and folksiness, suatu imbangan yang pelik antara keagungan dan kerakyatan, kesungguhan dan humor, kesenian dan drama, percaya diri sendiri, percaya akan rakyat, penggugatan terhadap negara-negara asing, kebijaksanaan umum, dan perincian untuk perbuatan tertentu.”
Setiap kali berpidato, paling sedikit ada tiga mikrofon di depan Sukarno. Satu untuk pengeras suara, satu dihubungkan dengan alat perekam, dan satu disambung ke Radio Republik Indonesia setempat. Sebelum mulai pidato, Sukarno minum seteguk air. Selama pidato, sekali pun dua jam lamanya, ia takkan minum lagi. Siapa pun yang mendengar niscaya kesirep. Belasan atau ribuan orang, semua bernasib sama: terpana. Belanda dan Jepang seolah beradu lelah dengannya. Antara siapa yang kapok berpidato atau menangkap.
Jika sudah tersiar kabar rapat akbar dihadiri Sukarno, rakyat dari beragam kelas akan merubung lokasi tempat ia akan berpidato. Bahkan tak sedikit yang sudah menginap satu malam sebelumnya, demi menanti singa podium tampil di hadapan mereka. Pidato Sukarno adalah paduan sempurna bakat seni menghibur, keterampilan ajaib berbicara, kecerdasan, kejeniusan, ketajaman visi, dan cinta-kasih. Ia pembicara tangguh, dan tahu persis apa yang akan dilakukannya usai pelantang suara dilungsurkan.
Seabad lebih telah berlalu. Gema suaranya masih terus menggelegar, berkobar, di jantung para pemuda Indonesia yang gelisah. Bapak, tabik kami untukmu. Sukarno sungguh benar menerapkan dawuh gurundanya, Cokroaminoto yang berkata, “Jika ingin jadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan, dan bicaralah bagai orator.”
Kelas pidato yang kami gelar di Sekolah Cerdik Cendekia, sejatinya berakar juga dari pesan keramat itu. Nampaknya saat ini, hampir tak ada lagi sekolah/guru yang mau menantang siswa-siswinya berpidato di depan kelas atau halaman sekolah. Maklum, sekolah kita sudah punya renjana lain. Setali tiga uang dengan industri. Wajar jika saat listrik padam pun, sekolah akhirnya diliburkan. Oh, mungkin yang libur itu sekolah kelistrik-listrikan kali ya.
Sebagai penutup, kami nukilkan sebuah dialog ringkas dengan seorang siswa kelas sembilan bernama Niko Saputra.
“Niko, apa perbedaannya kalau kamu belajar pakai Google dengan belajar sama orang yang memiliki ilmu?” tanya kami
“Kalau sama Google nteu aya proses bimbingan, Kak. Tidak bisa mengajukan pertanyaan bila bertemu titik bingung. Kalau sama orang yang sudah memiliki ilmu, kami bisa bertanya–dan saya juga lebih senang ngobrol dengan orang daripada ngobrol sama Google. Hehehe… []
Ren Muhammad
8 Agustus 2019